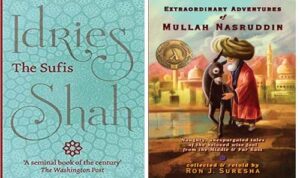Oleh Hasril Chaniago
(Wartawan Senior)
Tak banyak orang tahu bahwa Mohammad Natsir, Ketua Umum Partai Masyumi dan pernah menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia, adalah seorang wartawan yang pernah menjabat Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Ia juga menerbitkan dan memimpin surat kabar Abadi dan majalah Hikmah tahun 1950-an. Di hari tuanya, Natsir menerbitkan dan mengasuh majalah Media Dakwah yang menjadi penyalur pikiran-pikiran dan pendangannya terhadap berbagai persoalan bangsa dan umat.
Negarawan yang telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional ini sangat dekat dengan kalangan wartawan karena pernah pula menjabat Menteri Penerangan. Ia adalah tokoh besar dunia Islam yang sangat dihormati secara internasional. Berita kematiannya, disebut oleh bekas Perdana Menteri Jepang Takeo Fukuda sebagai “lebih dahsyad daripada jatuhnya bom atom di Hiroshima”.
Mohammad Natsir dilahirkan di Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatara Barat 17, Juli 1908, dari kedua orangtua yang berasal dari Maninjau, Kabupaten Agam. Sepanjang hayat Natsir diisi dengan tiga aktivitas: berorganisasi, menulis, dan berdakwah. Natsir juga seorang ninik mamak dalam kaumnya dengan gelar adat Datuk Sinaro Panjang.
Usia delapan tahun Nasir mulai belajar di HIS (Hollandsch Inlandsche School) Adabiah Padang, kemudian dipindahkan orang tuanya ke HIS pemerintah di Solok. Pada tahun 1923 Natsir meneruskan sekolah ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs/setingkat SMP sekarang) di Padang. Di sini Natsir menjadi anggota JIB (Jong Islamieten Bond) dan mulai bersentuhan langsung dengan gerakan perjuangan. Tamat dari MULO, pada tahun 1927, Natsir merantau ke Bandung untuk melanjutkan pendidikannya ke AMS (setingkat SMA). Ia mengambil jurusan Klasik Barat yang mengutamakan pelajaran bahasa Belanda, Inggris, dan bahasa Latin.
Selama di AMS ia juga sangat tertarik pada ilmu agama. Waktu luangnnya digunakan untuk belajar agama di Persatuan Islam (Persis) dengan bimbingan pendiri dan pemimpinnya Ustadz A. Hassan, seorang keturunan Arab kelahiran Singapura. Selain menjadi aktivis Persis, pada tahun 1932 Natsir mendirikan Pendidikan Islam (Pendis) sebagai perguruanIslam dengan sentuhan moderen. Sebagai cendekiawan muda Islam dan tokoh pergerakan, Natsir aktif menyebarluaskan gagasannya melalui tulisan. Sejak tahun 1930-an ia banyak menulis di majalah Pembela Islam dan Pedoman Masjarakat dengan nama samaran A. Moechlis. Ia menulis tentang Islam yang berkemajuan dan hubungan Islam dan negara.
Selama tahun 1938 hingga menjelang masa pendudukan Jepang, Natsir pernah terlibat polemik dengan Soekarno. Mereka berdebat mengenai posisi Islam dalam negara. Soekarno yang diasingkan di Ende, Flores, dan sedang keranjingan mempelajari Islam, kerap menulis di majalah Pandji Islam yang terbit di Medan. Di antaranya Soekarno menulis tentang “Memudakan Pengertian Islam”, “Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dan Negara” serta “Masjarakat Onta dan Masjarakat Kapal Udara”. Pada intinya tulisan Soekarno banyak menyerang kebekuan pemikiran Islam dan menganggap umat Islam di Indonesia terjebak dalam kekolotan.
Natsir membuat artikel balasan di Pandji Islam dan Al-Manaar, dengan seri artikel yang berjudul: “Tjinta Agama dan Tjinta Tanah Air”, “Ichwanu’shafaa”, “Rasionalisme dalam Islam”, “Islam dan Akal Merdeka”, dan “Parsatuan Agama dengan Negara”. Dalam seri artikel yang dibuatnya antara tahun 1939-1940 itu Natsir membeberkan pandangan dan sikapnya tentang Islam dan negara, rasionalisme, akal merdeka, dan cinta tanah air. Dalam salah satu tulisannya ia menerangkan bahwa aliran Mu’tazillah lebih progresif daripada rasionalisme dan akal merdeka yang diserukan Soekarno.
Pada zaman Jepang, Natsir bekerja di kantor Gubernur di Bandung sebagai Kepala Biro Pendidikan Kota Bandung (Bandung Shiyakusho). Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Natsir terpilih menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) sampai tahun 1946. Setelah itu ia diangkat sebagai Menteri Penerangan selama tiga periode (1946-1949) pada masa Kabinet Sjahrir II dan III serta Kabinet Hatta.
Akhir tahun 1949 Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil Konferensi Meja Bunda (KMB) di Den Haag, Negeri Belanda. Hatta menawari Natsir jabatan sebagai Perdana Menteri RIS. Tapi tawaran itu ditolaknya. Natsir yang menjabat Ketua Umum Partai Masyumi lebih memilih duduk di Parlemen RIS sebagai medan perjuangan. Ia menjabat sebagai Ketua Fraksi Masyumi di Parlemen.
Ketika menjadi anggota dan pimpinan Fraksi Masyumi di Parlemen RIS inilah Natsir menghasilkan karya bersejarah yang menentukan perjalanan bangsa Indonesia selanjutnya. Melalui mosi yang kemudian dikenal sebagai “Mosi Integral Natsir” ia menyampaikan tuntutan agar Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Mosi ini didukung oleh seluruh anggota Parlemen, sehingga pada tanggal 15 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara Republik Indonesia. Sangat mungkin karena jasanya inilah, Soekarno dan Hatta yang kembali menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, menunjuk Natsir menjadi Perdana Menteri pertama pasca-RIS. Natsir yang waktu itu masih berusia 42 tahun, menjabat kepala pemerintahan RI sejak bulan September 1950 sampai April tahun 1951.
Setelah berhenti sebagai Perdana Menteri, Natsir kembali ke Parlemen dan tetap memimpin Masyumi sampai tahun 1958. Di samping itu, ia meneruskan kegiatannya sebagai wartawan dan penulis. Pada tahun 1950, Natsir menerbitkan Harian Abadi dan Majalah Hikmah sebagai alat perjuangan politik dan ideologi, serta media untuk menyampaikan pikiran dan gagasannya. Tahun 1952, Natsir dipercaya sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI yang pertama dengan wakil Haji Agus Salim.
Ketika terjadi Pergolakan Daerah akhir tahun 1950-an, Natsir memilih bergabung dengan PRRI. Setelah tiga tahun hidup di hutan-hutan Sumatera Tengah, Natsir dan Syafruddin Prawiranegara turun gunung. Tapi setelah itu ia dikarantina, lalu ditahan berpindah-pindah ke Jawa Timur dan Jakarta. Penahanan Natsir bukan semata karena keterlibatannya dalam PRRI, tapi nampaknya berkaitan dengan sikapnya yang menetang Soekarno dan PKI yang waktu itu sangat berkuasa. Sebab, selain Natsir, Sjafroeddin dan Boerhanuddin Harahap, juga ditahan sejumlah tokoh nasional seperti Mohammad Roem, wartawan Mochtar Lubis, termasuk mantan Perdana Menteri RI yang pertama, Sutan Sjahrir, yang meninggal di Swiss ketika masih berstatus tahanan politik.
Meskipun mendapat perlakuan yang tidak adil, Natsir tak pernah berkurang kecintaannya kepada Republik Indonesia yang turut ia perjuangkan kemerdekaannya. Dari dalam tahanan, ia masih bersedia memberikan “memo” berupa secarik surat pada utusan Soeharto untuk diberikan kepada sahabatnya, Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdurrahman. Berkat surat Natsir itulah dapat dimulai pembicaraan dalam rangka memperbaiki ketegangan hubungan RI-Malaysia yang sempat tegang dipicu oleh Soekarno lewat aksi “Ganyang Malaysia”.
Keluar dari penjara, Natsir tidak lagi terjun ke politik dalam arti formal. Tokoh yang sangat dihormati oleh dunia Islam ini kembali ke pendidikan dan dakwah yang menjadi bagian dari nyaris sepanjang hidupnya. Pada Tahun 1967, bersama sejumlah ulama dan tokoh Islam, ia mendirikan dan memimpin Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di Jakarta. Pada tahun itu pula Natsir terpilih menjadi Wakil Presiden Muktamar Alam Islami yang bermarkas di Karachi, Pakistan. Selain itu, ia juga menjadi pengurus dan pernah menjadi Presiden Liga Muslim Dunia, dan sejak 1972 sebagai pengurus dan anggota Majlis A’la al-Alamy lil Masajid (Dewan Masjid se-Dunia). Kedua organisasi yang terakhir ini bermarkas di Mekah, Saudi Arabia.
Sebagai cendekiawan Islam, sartawan dan penulis yang produktif, Natsir banyak mewariskan ide dan pemikiran berharga. Semuanya tertuang dalam beberapa artikel yang jumlahnya tak terhitung, serta dalam bentuk buku yang tak kurang dari 20 judul. Di antara buku yang pernah ditulisnya adalah, Mohammad als Proveet (1931), Gauden Regels Regels uit den Quran (1932), De Islamietische Vrouw en haar Recht (1933), Cultuur Islam (bersama CP Wolf Kemal Schoemaker, Pendidikan Islam, 1936), Persatuan Agama dengan Negara (Padang, 1968), Islam dan Kristen di Indonesia (Pelajar, 1969), Capita Selecta (Bulan Bintang, 1973), The New Morality (disusun bersama SU Bajasut, 1969), dan Islam dan Akal Merdeka (Hudaya, 1970).
Setelah rezim berganti, dari Soekarno ke Soeharto, Natsir tidak pernah lagi terjun ke politik. Partai Masyumi yang pernah dipimpin dan dibesarkannya selama sembilan tahun (1949-1958), tidak pernah bisa dihidupkan lagi. Menjelang Pemilu 1971 ada kesediaan pemerintah mengizinkan pendirian satu partai politik untuk menampung aspirasi umat Islam, yaitu Parmusi. Namun pemerintah tak pernah mengizinkan para bekas tokoh eks Masyumi seperti Natsir, Roem atau Sjafroeddin ada dalam kepengurusan partai tersebut. Walhasil, Natsir hanya berada di luar gelanggang politik, dan menghabiskan hari-harinya untuk menulis, berdakwah dengan berceramah atau berkhotmat di berbagai tempat, terutama rutin dilakukannya di Masjid Al-Furqan di Jalan Kramat Raya. Selain itu, ia juga terus menulis di Media Dakwah yang didirikannya untuk mendukung kegiatan DDII.
Pada masa puncak “kejayaan” Orde Baru, dalam status dikucilkan karena sikapnya yang kritis terhadap rezim, negarawan besar yang memegang teguh Islam sebagai pandangan hidupnya ini, wafat di Jakarta pada tanggal 7 Februari 1993 dalam usia 84 tahun. Ucapan belasungkawa atas kematiannya datang dari segenap penjuru dunia. Bekas Perdana Menteri Jepang, Takeo Fukuda, mengirim telegram duka cita disertai kalimat “berita kematian Natsir lebih dahsyat daripada jatuhnya bom atom di Hiroshima”.
Setelah 10 tahun Reformasi, dan para pemilik dendam sejarah telah turun dari panggung kekuasaan bahkan pergi satu demi satu, baru terbuka kesempatan untuk menilai sosok dan peranan Natsir secara jernih dan objektif. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugrahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Mohammad Natsir.
(sumber: sumbarsatu.com)